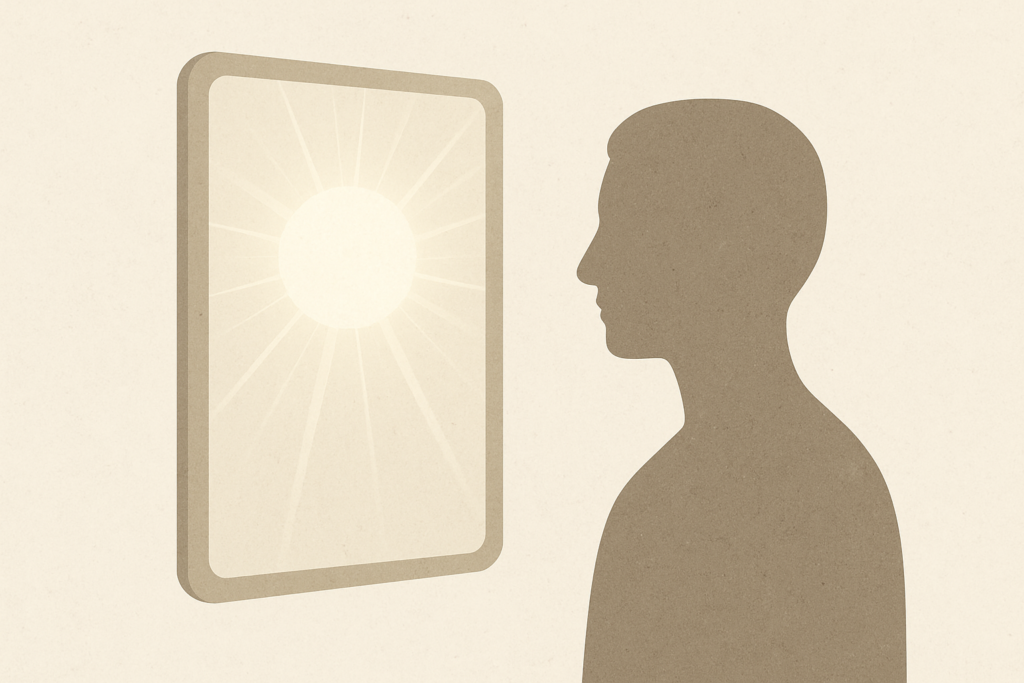Satu minggu yang lalu, saya memutuskan untuk membuka sebuah kursus Bahasa Inggris di tempat di mana saya dilahirkan. Saya tumbuh dan menyelesaikan studi tingkat dasar dan menengah di kampung ini. Saya bertekad mengabaikan semua tawaran yang lebih menggiurkan terkait keahlian dan prestasi yang telah saya raih, dan mengambil inisiatif mandiri untuk mengajar di kampung ini. Hal ini saya lakukan berdasarkan bocoran informasi yang saya dapat dari pihak pemerintah, bahwa bandara di kota kecil ini akan diperluas dan dijadikan bandara internasional karena letaknya yang secara geografis dekat antara Australia dan Indonesia. Selain itu, pemerintah juga bertekad menjadikan kota ini sebagai destinasi pariwisata. Di sisi lain, Bahasa Inggris kini telah menjadi syarat umum di beberapa kampus di Indonesia, di mana sertifikat Bahasa Inggris seperti IELTS dan TOEFL menjadi syarat utama dalam ujian akhir maupun pengambilan ijazah untuk beberapa jurusan di kampus-kampus yang telah menerapkan aturan tersebut.
Saya pun membuat flyer dan formulir pendaftaran yang ditujukan untuk anak-anak SD dari kelas satu sampai kelas enam. Karena sekolah masih libur, saya meminta adik laki-laki saya untuk menyampaikan rencana saya yang tulus dan ikhlas ini melalui ruang informasi gereja agar dapat diumumkan kepada jemaat. Setelah pengumuman dilakukan—dan termasuk menyebutkan tarif sebesar Rp300.000 per bulan—seorang pastor paroki (karena gereja saya di kampung ini telah menjadi paroki) menyampaikan pendapatnya: “Ilmu itu seharusnya gratis,” katanya. Ia juga menambahkan, “Saya juga telah membuka kursus agama dan setiap sore siswa harus datang kepada saya untuk pengayaan agama.” Pernyataan tokoh agama ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan, ada pula yang mulai bersungut-sungut soal tarif yang saya berikan. Hal ini benar-benar sempat merusak semangat dan suasana hati saya untuk memberikan yang terbaik bagi suku bangsa saya sendiri.
Di lain sisi, saya juga menyadari adanya berbagai budaya yang dibawa oleh orang-orang atau beberapa pihak yang datang dari luar dan bertentangan dengan nilai luhur dan spiritualitas masyarakat kami di atas tanah ini, yang menurut saya telah melenceng jauh dari kehidupan leluhur kami yang memiliki spiritualitas tinggi. Contohnya, mereka membawa budaya minum-minuman beralkohol dan berpesta sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Budaya ini perlahan masuk dan mulai dianggap lumrah, bahkan dijadikan tolok ukur gaya hidup yang “keren” dan maskulin. Mereka bahkan menjual minuman keras demi meraup keuntungan, dan sebelumnya memengaruhi psikologis masyarakat saya—bahwa mabuk itu adalah hal yang wajar, modern, bahkan identik dengan kejantanan. Padahal, mereka sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatifnya, seperti kerusakan perkembangan otak dan gangguan sistem saraf jika dikonsumsi secara berlebihan. Saya bisa memahami, mungkin mereka enggan membicarakan risiko tersebut karena takut kehilangan sumber pendapatan. Bisa jadi, itu satu-satunya mata pencaharian yang mereka andalkan selama di Papua ini. Dengan demikian, saya mulai mengambil kesimpulan bahwa tidak semua bangsa yang masuk ke Papua datang dengan niat yang baik, tulus, dan murni secara batin. Ada yang datang hanya untuk mengambil keuntungan semata, dan untuk itu mereka rela membiarkan masyarakat tetap hidup dalam ketidaktahuan. Mereka tidak peduli seberapa jauh praktik ini bisa menghancurkan Sumber Daya Manusia suatu bangsa—secara perlahan, tapi pasti.
Penjelasan Ilmiah Singkat yang mendukung statemen saya bahwa itu merusak Sumber Daya Mnausia adalah:
Alkohol bersifat neurotoksik; Artinya, alkohol bisa merusak sel-sel saraf (neuron) di otak. Otak tidak punya kemampuan regenerasi sebesar organ lain, jadi kerusakannya bisa permanen.
- Menyusutkan volume otak
Studi pencitraan otak (MRI) menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi alkohol berat dalam jangka panjang mengalami penyusutan volume otak, khususnya di bagian yang mengatur memori, perhatian, dan kontrol diri (korteks prefrontal dan hippocampus).
- Gangguan fungsi kognitif dan emosi
Efeknya bisa berupa: Penurunan kemampuan belajar, Hilang focus, Sulit membuat keputusan logis, Emosi tidak stabil, dan Perilaku impulsif
- Dampak pada otak remaja lebih besar
Otak manusia baru selesai berkembang sepenuhnya sekitar usia 25 tahun. Jika remaja mengonsumsi alkohol, perkembangan otak mereka bisa terganggu, terutama pada kemampuan berpikir abstrak, perencanaan, dan pengendalian diri.
Contoh Nyata Kerusakan Otak Akibat Alkohol:
Wernicke–Korsakoff Syndrome: Gangguan otak akibat kekurangan vitamin B1, sering terjadi pada pecandu alkohol. Gejalanya: kebingungan, hilang ingatan, sulit bicara. Alcohol-Related Dementia: Demensia atau kepikunan dini yang disebabkan oleh konsumsi alkohol berat jangka panjang. Blackout atau Amnesia sementara: Lupa total apa yang terjadi saat mabuk.
Dari kejadian dan semua yang saya amati, muncul beberapa hal di benak saya dan menghasilkan pernyataan sekaligus pertanyaan seperti:
“Kita ini bukan roh yang melayang-layang di udara sambil mengajar dan berbicara. Kita ini manusia—roh yang tinggal dalam tubuh—yang membutuhkan nutrisi dari makanan, dan makanan itu dibeli dengan uang agar kita tetap sehat dan berstamina untuk melanjutkan misi kita menyebarkan kebaikan, bukan? Dan kita harus adil bukan hanya perihal memelihara roh atau jiwa kita tetapi juga tubuh kita juga membutuhkan pemeliharaan yang sehat.”
Apalagi tarif yang saya tetapkan itu, menurut saya, sudah sangat murah dan terjangkau. Di kota-kota besar, kursus semacam ini bahkan sudah dipatok Rp300.000 per jam, dan ada pula yang mencapai Rp tiga juta per bulan. Jangankan di kota besar, semenjak bocoran bahwa kota kecil ini akan dijadikan kota pariwisata oleh pemerintah tarif yang sama untuk kursus Bahasa Inggris pun diberlakukan oleh beberapa pihak yang bukan merupakan pribumi. Dlagian, dari uang Rp300.000 itu pun tidak sepenuhnya masuk ke kantong saya, karena saya masih harus membeli berbagai kebutuhan penunjang proses belajar, seperti tinta, papan tulis dan spidol, kertas, serta beberapa bahan praktik yang akan digunakan oleh para siswa selama kursus berlangsung.
Ditambah lagi, pengalaman hidup saya sendiri yang menjadi latar belakang munculnya judul: “Gereja seharusnya menjadi tempat melahirkan manusia beriman, bukan tempat menyebarkan roh ketakutan.”
Saya berasal dari latar belakang seperti mereka. Saya tumbuh di kampung yang sama, bersama orang-orang yang sebagian besar hidup dalam kesederhanaan, bahkan keterbatasan. Saya tahu, tidak semua orang tua sanggup menghasilkan Rp300.000 dalam sebulan. Tapi berdasarkan pengamatan saya, sering kali kesulitan itu bukan semata karena tak ada uang, melainkan karena prioritas yang keliru.
Banyak orang tua lebih memilih mempertahankan kebiasaan yang merusak—budaya “toxic” yang diwariskan turun-temurun—daripada memikirkan gizi anak-anak mereka agar otaknya berkembang sehat, dan mampu menerima pelajaran di sekolah dengan baik. Saya sering melihat, seorang ayah bisa sering membiarkan anaknya makan mi instan atau nasi saja tanpa lauk, sambil terus merokok. Atau, setelah panen selesai, bukannya uang itu digunakan untuk kebutuhan keluarga, justru sebagian besar habis untuk berfoya-foya dan mabuk-mabukan.
Mereka tidak peduli apakah anaknya makan cukup atau tidak, apakah kebutuhan nutrisi terpenuhi, apakah ada bakat terpendam dari anak mereka yang perlu dikembangkan. Kesadaran itu tidak ada. Yang ada hanyalah pelarian dari tanggung jawab, dalam bentuk kenikmatan sesaat. Parahnya lagi, ketika anak orang lain—atau katakanlah anak tetangga—lebih sukses dari anak mereka sendiri, sebagian orang tua justru membanding-bandingkan, merendahkan anaknya, dan lupa bahwa kegagalan itu bisa saja bermula dari diri mereka sendiri yang enggan berbenah.
Mereka tidak tahu betapa besar pengorbanan orang tua dari anak-anak yang sukses itu. Demi masa depan anak-anaknya, orang tua seperti itu rela meninggalkan budaya negatif—hal-hal yang sudah lama menjadi kebiasaan mereka—demi pertumbuhan, perkembangan, dan kestabilan emosional anak-anak yang mereka lahirkan sendiri. Mereka sadar bahwa menjadi manusia beriman berarti berani kehilangan hal-hal yang merusak, seperti minuman keras, rokok, dan gaya hidup konsumtif lainnya—demi sesuatu yang lebih bernilai: pendidikan, harapan, dan masa depan anak.
Mereka tidak takut terlihat miskin dan mengedepankan gengsi dalam kehidupan toxic yang dianggap lumrah demi bisa membeli buku yang mahal, kamus yang tebal, atau alat musik seperti piano dan gitar jika anaknya menunjukkan bakat dan masih banyak lagi. Mereka mungkin tidak bisa membeli semuanya sekaligus, tapi mereka menabung dan memprioritaskan—karena mereka tahu, pengorbanan hari ini akan berbuah baik di masa depan.
Sedangkan aku, aku menyeimbangkan pengorbanan orang tuaku dengan hidup dalam iman—dengan tidak takut kehilangan teman-teman toxic yang berpotensi merusak masa depanku. Aku berani menarik diri dari keramaian dan kebisingan dunia yang menurutku tidak penting. Aku tidak peduli jika dianggap aneh, hanya karena aku sedang mencari bimbingan Ilahi untuk pengembangan potensi diri. Aku menggunakan uang yang diberikan oleh kedua orang tuaku untuk hal-hal positif yang membangun diriku. Aku tidak menggunakannya untuk memenuhi gengsi, memuaskan ego, atau membeli minuman keras, merokok, apalagi melakukan hubungan bebas hanya agar dianggap keren dan diterima oleh dunia yang beracun. Aku tahu bahwa hidup dalam iman adalah tentang berani meninggalkan semua yang tidak baik demi sesuatu yang lebih baik, demi kebaikanku sendiri—secara rohani, mental, dan masa depan. Aku percaya pada hukum alam semesta: “Hukum Tarik-Menarik”—bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan secara positif, akan menarik hal-hal positif pula ke dalam hidup kita. Keyakinan ini selaras dengan apa yang dikatakan Yesus: “Jangan khawatir tentang semua yang kau keluarkan hari ini, karena semuanya akan dikembalikan padamu dua kali lipat.” Karena aku sekarang mendapatkan banyak kelimpahan, baik secara potensi, bakat, karir, dan semua hal yang orang lain anggap keajaiban ada dan terjadi di dalam hidup saya.
Dan setelah menjalani hidup dan mengamati banyak hal, aku semakin yakin bahwa hukum alam semesta, “Hukum Sebab Akibat” dan kata-kata Yesus berjalan seiring: “Apa yang kamu keluarkan, itulah yang akan kamu terima.”
Jika kita menghabiskan uang, waktu, dan energi untuk hal-hal negatif, maka yang datang kepada kita pun akan dipenuhi oleh energi negative dan dipenuhi ksialan juga kejadian-kejadian negative bahkan orang-orang yang negative dan selaras dengan frekuensi dan vibrasi energimu yang semuanya masih masuk dalam hukum alam semesta, “Hukum Tarik Menarik”. Karena pada akhirnya, kita hanya akan menerima apa yang kita berikan kepada semesta. Aku percaya bahwa Tuhan bekerja melalui getaran—melalui keselarasan batin, tindakan, dan niat. Tidak peduli seindah apa pun kata-kata yang kamu susun di depan altar saat menyampaikan harapan dan doa-doamu, jika perbuatanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak selaras dengan doamu, maka kamu—atau anak-anakmu kelak—tidak akan melihat keajaiban itu hadir dalam hidup.
Sebagai penutup, bahkan Bunda Maria pun tidak membutuhkan validasi dari Bait Allah untuk mengandung dan melahirkan dari Roh Kudus. Ia melakukan pekerjaan batin yang dalam dan mempertahankan prinsipnya sebagai sosk feminine yang sehat secara tubuh dan jiwa, hingga ia terpilih sebagai perawan pilihan Allah. Yesus pun tidak membutuhkan daftar nama dari Bait Allah atau persetujuan dari para pemuka Bait Allah untuk memilih kedua belas murid-Nya. Mereka dipilih karena takdir dan pertemuan Ilahi, untuk membuktikan kebesaran Tuhan kepada umat manusia. Maka, kamu juga tidak membutuhkan validasi, izin, atau penerimaan dari seorang tokoh agama atau pihak gereja untuk melakukan hal-hal yang baik, bijak, tulus, dan murni baik untuk dirimu sendiri mau pun bagi orang lain. Karena dengan begitu, kamu justru menujukan bentuk kasih paling dalam yang hanya bisa lahir dari hati yang selaras dengan Sang Ilahi.
Jika Yesus berkata, “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar,” maka kamu pun berhak menerima hasil dari penawaranmu yang tulus, ikhlas, dan penuh pengorbanan. Itu adalah sesuatu yang adil dan sah, bahkan sesuai dengan hukum-hukum alam semesta—karena alam semesta selalu menuntut keadilan dan keselarasan. Selama uang hasil keringat para orang tua diberikan dengan niat tulus demi kebaikan anak-anak mereka, dan kamu menggunakannya dengan bertanggung jawab—bukan untuk hal-hal negatif—maka justru dari situlah berkat akan mengalir. Tuhan sendiri menjanjikan masa depan yang berlimpah bagi mereka yang memberi dengan kasih, dan bagi mereka yang melayani dengan hati yang murni.
Jika banyak orang di luar sana menggunakan agama sebagai topeng bagi kejahatan dan kebusukan yang mereka sembunyikan, dan mengartikan isi kitab suci sesuai kepentingan pribadi atau tidak berdasarkan pengalaman iman yang mendasari isi kitab suci dan menyebarkan roh ketakutan, mengapa justru yang datang dengan kejujuran, keterbukaan, dan keikhlasan dianggap sebagai ancaman?
Yohanes Kabes, S.S (B.A. in English Literature) is a Melanesian writer, novelist, and poet. His writings and articles focus on themes of spirituality and the inner journey of the human soul — the awakening of consciousness. He also analyzes literary works through psychological and spiritual perspectives, believing that life itself is the philosophy of the universe. In his novels, Kabes often explores the realms of horror, thriller, and mystery. He is also the first to design fashion pieces inspired by his own poetry.