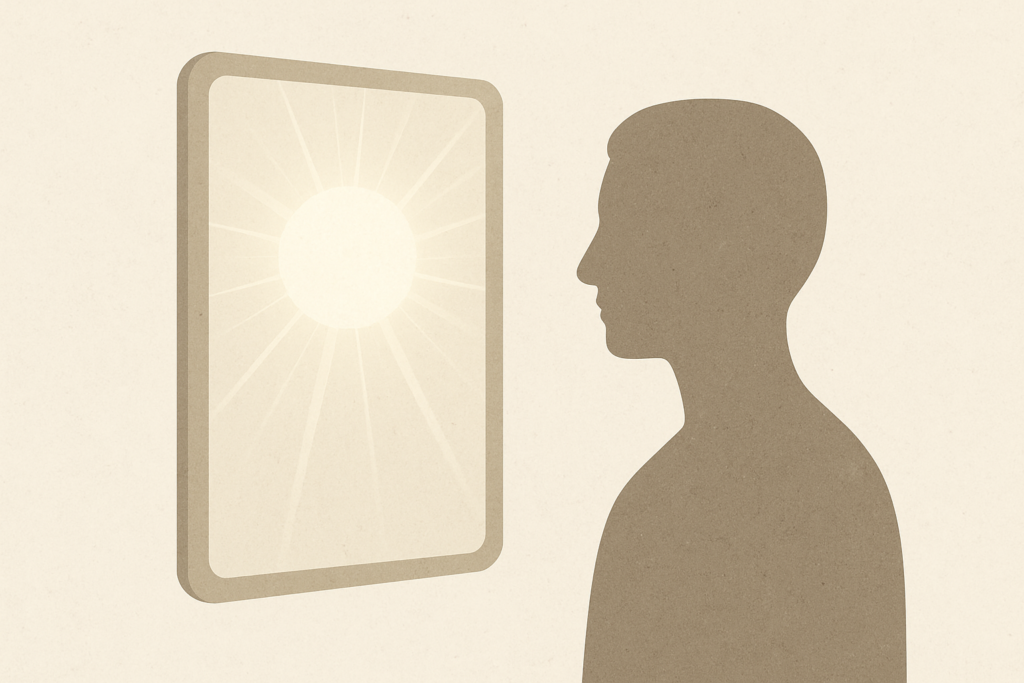“Defenisi manuasia biasa yang anda maksudkan itu seperti apa dan defenisi manusia biasa di mata Tuhan itu seperti apa?”
Istilah ‘Manusia Biasa’ di lingkungan yang toxic sering dijadikan tameng untuk melanggengkan kebiasaan beracun yang telah mendarah daging—sebuah kenyamanan dalam kehancuran. Ironisnya, kata ini juga sering muncul dalam kotbah-kotbah gereja, sebagai justifikasi atas kebusukan hati, seolah-olah orang-orang yang memakai kesucian dan gereja sebagai topeng kejahatan adalah mereka yang paling layak diampuni. Namun pengampunan semacam itu—tanpa perilaku bercermin yang sejati—tidak pernah membebaskan mereka dari kebiasaan kotor yang mencemari hati, nurani, dan bahkan DNA mereka. Sebaliknya, mereka justru mewariskan kutukan, menciptakan siklus beracun yang terus berulang di dalam pola keturunannya dan terus menggunakan gereja dan tradisi sucinya untuk melindungi diri dari perubahan palsu yang meraka bangun dengan hati-hati demi reputasi manusia paling baik di hadapan dunia dan manusia.
Pertumbuhan batin memang menyakitkan. Karena syarat utamanya adalah: berani menghadapi diri sendiri yang asli. Dan sayangnya, banyak manusia justru lebih nyaman hidup di balik topeng—menciptakan versi palsu dari diri mereka sendiri dan sibuk melabeli orang lain dengan pandangan terbatas yang mereka miliki. Mereka menyembunyikan luka, kedengkian, dan ketakutan di balik pelaksanaan tradisi suci. Bukan untuk mengalami pembaruan batin, melainkan untuk melindungi reputasi palsu yang dengan hati-hati telah mereka bangun demi diterima oleh lingkungan. Itulah mengapa topeng-topeng religius begitu marak: karena lebih mudah terlihat kudus di mata manusia daripada jujur di hadapan Tuhan. Cukup duduk diam dan mengamati, maka semua inkonsistensi itu akan tampak. Mulut yang berkata manis di bait Allah tak pernah sejalan dengan perilaku dan nurani di luar tembok gereja.
Apa yang mereka khotbahkan tentang kasih, kejujuran, dan pengampunan tak pernah benar-benar dihidupi. Semua hanya pertunjukan. Ritual tanpa roh. Kebenaran tanpa kehidupan. Sembari melindungi diri dibalik label, “Manusia Biasa”.
Lalu, apa definisi ‘manusia biasa’ bagi Tuhan? Jawabannya: tidak ada.
Sebab Tuhan sendiri tidak pernah menitipkan roh kehidupan (bagian dari dirinya) untuk menjadikan manusia sebagai makhluk biasa. Ia menyentuh manusia menjadi makhluk yang sempurna—memiliki nurani, kesadaran spiritual, dan kapasitas untuk terhubung dengan-Nya secara sakral. Tanpa perantara. Tanpa ritual buatan manusia. Tanpa syarat sosial. Dan yang paling penting: gratis.
Hubungan itu tidak membutuhkan topeng. Tidak butuh pengakuan dari komunitas atau validasi dari dunia religius yang sudah lama kehilangan kepekaan dan sensor nurani dalam diri. Tuhan tidak pernah meminta kita menyamar untuk diterima. Tuhan tidak pernah mengajar kita berpura-pura untuk terlihat kudus. Yang Dia inginkan adalah hati yang jujur, jiwa yang mau kembali pada kemurniannya, dan keberanian untuk melepaskan warisan luka yang menyamar sebagai “kebiasaan rohani”.
Lalu, mengapa kata ‘Manusia Biasa’ begitu sering digunakan?
Jawabannya sederhana namun menyakitkan: karena banyak orang tidak mau menghadapi diri mereka sendiri. Mereka menolak rasa sakit yang seharusnya menjadi jalan masuk menuju pertumbuhan batin. Lebih mudah bagi mereka menyakiti diri sendiri demi cinta yang palsu, demi penerimaan semu, dan demi memperkokoh topeng yang telah mereka kenakan selama bertahun-tahun. Topeng itu akhirnya menyatu, menjadi wajah kedua—dan bahkan mereka sendiri lupa siapa sebenarnya yang ada di baliknya.
Daripada memilih luka sebagai simbol pertumbuhan spiritual, mereka memilih kenyamanan semu sebagai pelindung. Mereka lebih suka kelihatan kuat di hadapan manusia, daripada hancur dan diperbaiki oleh Tuhan. Padahal justru di titik kehancuran itulah roh manusia paling jujur berseru dan paling layak disentuh oleh kasih ilahi.
Manusia biasa itu punya nurani. Jika seseorang sampai memiliki niat untuk menyakiti orang lain—baik secara terang-terangan maupun dengan cara yang licik, tertutup, dan terselubung—maka ia telah menanggalkan kemanusiaannya. Itu bukan lagi manusia. Bahkan bukan manusia biasa. Melainkan peliharaan iblis yang jinak, yang hidup nyaman di balik topeng moralitas dan tradisi suci. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika gereja ikut menormalisasi kebusukan hati seperti itu.
Ketika kata-kata manis dilantunkan di depan altar, tetapi isinya adalah kepalsuan dan racun. Ketika topeng kesucian dipakai bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk melindungi kejahatan yang sistematis dan terorganisir. Lebih tragis lagi—orang-orang yang jujur, yang hidup selaras dengan hati dan nurani, justru direndahkan, dijauhi, bahkan dikutuk. Seolah kejujuran adalah dosa, dan berpura-pura adalah syarat diterima di tengah jemaat.
Jika mereka yang jujur tentang siapa diri mereka—yang hidup selaras dengan jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan—justru datang ke gereja hanya untuk dikutuk, dikhotbahi, dan dihakimi…
Maka pertanyaannya adalah: Mengapa mereka yang datang dengan kebusukan hati dan topeng justru dilindungi dan dipandang layak? Seolah Tuhan lebih mencintai kepalsuan, lebih menyayangi ketidaksinkronan antara hati dan laku, dan lebih menghargai kemunafikan yang terorganisir daripada kejujuran yang hancur dan tulus. Apakah kasih Tuhan kini hanya berlaku bagi mereka yang pandai berpura-pura dan bertopeng?
Apakah gereja telah lupa bahwa yang kudus bukanlah yang bersih, tapi yang jujur tentang sisi buruknya tapi selaras dengan terangnya?
Bukankah manusia diciptakan untuk hidup selaras—seimbang dengan seluruh sisi dalam dirinya: terang dan gelap, luka dan harapan, kelemahan dan kekuatan?
Bukankah panggilan sejati manusia adalah menjadi utuh, bukan sempurna?
Tetap berdiri teguh dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diperoleh dari perjalanan hidup, tanpa harus mengubah jati diri hanya karena gereja memaksa? Namun yang sering terjadi adalah: gereja tak lagi merangkul keutuhan manusia. Sebaliknya, ia menuntut kepalsuan sebagai syarat diterima.
Manusia pun dipaksa memelihara topeng, belajar menjadi aktor rohani, dan tanpa sadar membiasakan kemunafikan—bukan hanya di hadapan sesama, tetapi di hadapan Tuhan. Dan itulah tragedi spiritual paling sunyi: Ketika seseorang merasa harus berpura-pura bahkan dalam doa bahkan sampai harus mengorbankan orang lain demi keutuhan palsu dan kerekatan topeng yang dikenakan.
Yohanes Kabes, S.S (B.A. in English Literature) is a Melanesian writer, novelist, and poet. His writings and articles focus on themes of spirituality and the inner journey of the human soul — the awakening of consciousness. He also analyzes literary works through psychological and spiritual perspectives, believing that life itself is the philosophy of the universe. In his novels, Kabes often explores the realms of horror, thriller, and mystery. He is also the first to design fashion pieces inspired by his own poetry.